
Selayang Pandang
Desa Pantai Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong
Tentang Muara Gembong Survive
Persoalan kawasan hutan dan pertanahan/agraria dalam arti luas bukanlah persoalan yang secara langsung terjadi hari ini atau kemarin, namun persoalannya terakumulasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Manifestasinya dapat dilihat dari berbagai bentuk, seperti konflik antar berbagai pihak, keterlanjuran tambang, dan kebun dan pemukiman di seluruh fungsi hutan (konservasi, lindung, dan produksi), persoalan tukar menukar kawasan hutan, perizinan yang salah, hilangnya kekayaan negara dan tingginya biaya transaksi perizinan, serta pelanggaran hak asasi manusia.




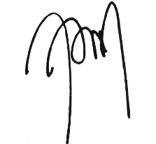

Tulisan ini mengulas bagaimana persoalan kawasan hutan dan pertanahan telah berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Persoalan ini sejatinya tidak hanya dapat dilihat dengan menggunakan perspektif yang sempit, namun perlu adanya perspektif secara histori yang lebih luas lagi. Dengan narasi yang sangat singkat ini, kami berharap dapat membuka pandangan baru atas persoalan ini. Semoga tulisan dengan judul “Selayang Pandang Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong” dapat membuka pintu manfaat bagi masyarakat banyak.
Hutan sebagai salah satu sumber daya alam, pengelolaannya secara mendasar diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konsepsi penguasaan oleh negara digunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kemakmuran rakyat yang maksimum. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang dihimpit oleh dua benua dengan kepemilikan lebih dari 17.000 pulau, pemerintah mengalokasikan 120,4 juta hektar dengan persentase 62,97% luas daratannya sebagai kawasan hutan, Ringkasnya, dari total luas wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 37,03% ditetapkan sebagai bukan kawasan hutan (KLHK 2019). Ketimpangan alokasi penggunaan tanah tersebut telah banyak ditentang dengan menggunakan asas efisiensi dan keadilan. Seyogyanya faktor historis berperan besar dalam menghendaki ketimpangan alokasi tanah di Indonesia saat ini.
Pemerintah Hindia Belanda mengubah struktur agraria secara signifikan sebagai akibat dari kebangkrutan VOC dan berakhirnya pemberlakuan tanam paksa (cultuurstelsel). Dasar perubahannya adalah dengan adanya penetapan Boschordonatie voor Java en Madura 1865 dan Agrarische Wet 1870. Setidaknya, kedua regulasi tersebut menjadi permulaan dalam menghancurkan sistem-sistem lokal penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Seluruh tanah (termasuk hutan) yang tidak dimiliki dengan hak eigendom (tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya) merupakan milik negara (domeinverklaring). Konsekuensi logis atas konsepsi ini adalah negara memiliki semua tanah rakyat dengan sebutan apapun, apabila tanah tersebut tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom.


Pemerintah membuat batas klasifikasi penggunaan tanah negara menjadi dua, yaitu hutan (kawasan hutan) dan bukan hutan (tanah pertanian, perkebunan, dsb). Hal yang menarik adalah kawasan hutan yang diklaim tidak hanya sebatas tanah dengan tutupan lahan berupa hutan secara biofisik, namun juga mencakup tanah yang tutupan lahannya bukan berupa hutan seperti semak, belukar, dan tanah-tanah lainnya yang tidak ditumbuhi tanaman berkayu. Tanah-tanah ini peruntukannya adalah tersedianya cadangan kebutuhan pengembangan tanaman kayu dan perlindungan alam. Artinya, klaim kawasan hutan tidak hanya didorong oleh narasi ekonomi (produksi), namun juga melibatkan narasi-narasi perlindungan alam. Maka dari itu, watak utama klaim kawasan hutan adalah perampasan teritori sekaligus penghancuran sistem- sistem lokal tentang hak berlapis atas lahan dan produk hutan (Peluso 2006).


Klaim kawasan hutan secara efektif dioperasionalisasikan di Pulau Jawa dimana Pulau Jawa dikenal sebagai hutan politik tertua di Indonesia (Vandergeest & Peluso 2001). Klaim kawasan hutan dilakukan dengan cara penyerahan pengelolaan kepada badan/lembaga pemerintah, lalu kemudian serangkaian operasi manajemen hutan dilaksanakan. Operasi tersebut mencakup identifikasi dan inventarisasi tanah-tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan, penentuan batas wilayah, dan pembagian areal kerja. Tindakan ini bersifat teknis, namun sesungguhnya kental akan muatan politis berupa pembatasan akses masyarakat terhadap pemanfaatan lahan dan produk hutan. Lebih buruk lagi, pendekatan adminsitratif dan koersif diterapkan sebagai kontrol dan kendali atas wilayah. Maka dari itu, masyarakat yang melanggar aturan formal seringkali disudutkan dengan sebutan-sebutan yang memojokkan seperti pencuri, perambah hutan, maupun sebutan lainnya. Hal ini juga turut serta menegaskan bahwa kehutanan berwatak bengis, asosial dan ahistoris


Persoalan klaim kawasan di masa lalu pada akhirnya berdampak besar pada kondisi saat ini. Kasus di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu contohnya. Desa tersebut saat ini termasuk ke dalam kawasan hutan lindung sebagai akibat dari klaim kawasan oleh pemerintah di masa lalu. Aktivitas masyarakat dan pengembangan potensi desa menjadi terhambat karena harus menghadapi proses izin yang panjang dan sulit. Mereka masih belum mempunyai hak kepemilikan padahal mereka membayar pajak rutin setiap tahunnya. Maka, persoalan keadilan dan kesejahteraan menjadi pertanyaan besar saat ini. Tulisan ini akan memaparkan bagaimana sejarah kepemilikan lahan, masyarakat, dan perkembangan kawasan di Desa Pantai Bahagia secara khusus dan Kecamatan Muara Gembong secara umum.


Muara Gembong Survive
Menggambarkan kehidupan nelayan dan hasil tambak yang melimpah. pada tahun 1980-an sebelum dampak eksploitasi menghantam daerah ini
Alamat
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Jam
Senin - Jumat